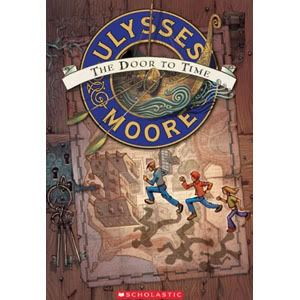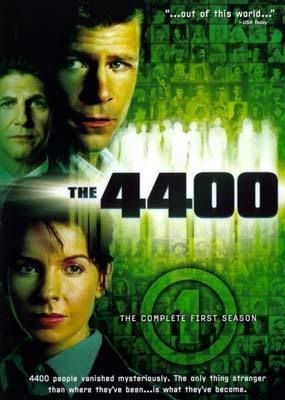Kucing, Tukang Sate, dan Azab Tetangga Pemakan Tanah Orang
Masih ingat cerita saya tentang tetangga nenek saya yang membangun rumah di atas tanah milik negara? Kalau lupa, baca lagi yang ini.
Sebelum nyangkut di Semarang, tempat berlangsungnya pernikahan sepupu saya, saya menyempatkan mampir ke Magelang. Ya kan saya harus ngejemput nenek dulu. Selain itu, saya juga ingin tahu beberapa hal.
- Kucing nenek saya, Ichigo. Dia tuh kucing nenek saya yang paling cakep. Waktu saya tinggalkan dulu, dia lagi lucu-lucunya. Kalau cowok, mungkin sekitar 20-an, tuh. Saya sudah berharap-harap bisa mengelus-elus dan ngajak main dia. Sayangnya, niat saya nggak kesampaian. Ichigo sudah mati dikeroyok anaknya. Heh? Emangnya Ichigo ayah durhaka dan suka memukuli anaknya sampai ia mati dikeroyok anaknya sendiri?
- Rumah yang ada di depan rumah nenek saya sudah jadi. Itu berita bagusnya. Berita buruknya, tidak ada yang akan menempati rumah itu. Kenapa? Rumah itu rencananya akan diberikan kepada anak pemilik rumah. Sang anak akan bekerja di kantor pemda Magelang, dan agar si anak hidup dengan tenang dan damai, sang ayah yang merupakan pejabat di kota lain, memutuskan untuk membangunkannya sebuah rumah. (Tanpa peduli tanah itu dibangun di atas taman kota yang seharusnya nggak boleh dibangun untuk rumah) Tapi keinginan itu tidak pernah terwujud karena si anak meninggal hanya beberapa hari sebelum hari pernikahannya.
"Kecelakaan, Bbu. Waktu mbayar atau beli apa gitu naik motor. Ditabrak mobil dari belakang," kata tukang sate langganan nenek saya sambil mengipas-ngipas satenya. Weih. Tukang sate ini canggih juga layanan berita gosipnya. Sampai tahu segala.
"Terus rumah ini mau diapakan?"
"Ya nggak tahu. Bapaknya sekarang stres."
"Iyalah. Siapa yang nggak stress. Anaknya mau kerja di pemda. Sudah mau menikah, mendadak meninggal."
"Itulah, Bu kalau jadi orang nggak bener. Sewenang-wenang. Mbangun rumah ngambil tanah rakyat."
Saya lantas mengamati rumah itu di antara kepulan asap sate. Dulu, saya termasuk yang sangat membenci rumah itu. Sudah dibangun di atas tanah yang diperuntukkan untuk taman kota, masih mengambil jalan gang lagi. Mungkin bukan cuma saya yang merutuki rumah itu, tapi semua penghuni gang beserta anak cucunya.
Tapi sekarang, saya merasa kasihan.
Kasihan pada rumah itu karena akhirnya mubazir. Rumah itu sudah dibangun melalui banyak paksaan dan ketidakrelaan dari warga. Pembangunan rumah itu banyak melibatkan emosi. Emosi warga, maksudnya. Tapi, saya lebih kasihan pada keluarganya. Calon pemilik rumah ini adalah anak satu-satunya. Lantas, untuk apa semua kekayaannya kalau tidak ada ada keturunan yang bisa menikmatinya?
Meski si tukang sate yakin kejadian ini balasan dari Tuhan, hati kecil saya kok tidak tega untuk menyetujuinya. Kematian, bagaimanapun juga adalah sebuah takdir. Hanya saja, mungkin Tuhan ingin menyentil telinganya. Agar jangan main-main dengan kekuasaannya. Agar jangan jadi orang yang semaunya sendiri.

 dee. twenty something. single. a wannabe writer who's currently stuck living an editor's life. always have the perfect reason not to write. love lavender, cheese, tiramisu, tea, and cats. thinking of becoming a cheetah in the next life. current cat pet: 0. current dead cat pet: 5
dee. twenty something. single. a wannabe writer who's currently stuck living an editor's life. always have the perfect reason not to write. love lavender, cheese, tiramisu, tea, and cats. thinking of becoming a cheetah in the next life. current cat pet: 0. current dead cat pet: 5